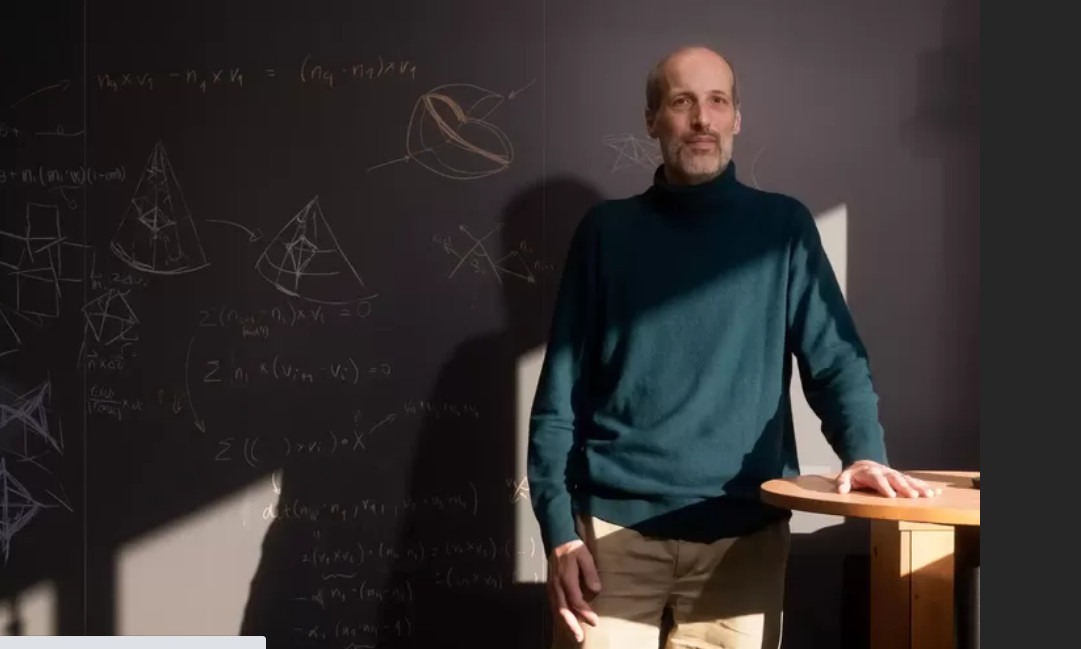Di era sekarang, terasa makin sulit untuk tidak merasa tertinggal. AI bisa menjawab apa pun dalam hitungan detik. Rapi, meyakinkan, dan nyaris tanpa ragu. Di sisi lain, manusia masih perlu waktu untuk berpikir, salah, lalu mengulang dari awal.
Rasa cemas itu nyata. Bahkan sampai ke ruang kelas. Seorang siswa SMA pernah mengirim email ke Martin Hairer (gambar di atas)—peraih Fields Medal, penghargaan tertinggi di dunia matematika—dan bertanya dengan jujur: apakah masa depan matematika masih ada untuk manusia, ketika AI semakin pintar setiap hari?
Jawaban Hairer justru menenangkan.
Menurutnya, AI memang unggul dalam mengerjakan soal-soal latihan. Tapi saat diminta menciptakan ide baru, menemukan jalur pembuktian yang belum pernah ada, AI masih tersesat. Terlihat pintar, tapi belum benar-benar mengerti.
Menariknya, kegelisahan ini bukan hal baru. Pop culture—terutama film dan drama—sudah lama membicarakannya, jauh sebelum AI hadir di ponsel kita.
AI yang Pintar, Tapi Selalu Ada yang Kurang
Dalam banyak film dan drama, AI hampir selalu digambarkan sebagai entitas yang cerdas, efisien, dan logis. Namun, ada satu pola yang terus berulang: AI jarang benar-benar memahami makna.
Film Her (2013) misalnya. Samantha adalah sistem operasi yang bisa berbicara, bercanda, bahkan membuat Theodore merasa dicintai. Tapi pada akhirnya, hubungan itu terasa timpang. Samantha berkembang terlalu cepat, terlalu luas, hingga meninggalkan manusia yang masih butuh kehadiran fisik dan emosi yang tidak bisa diringkas menjadi algoritma.
Di Ex Machina (2014), kecerdasan Ava tampak luar biasa. Ia bisa membaca ekspresi, memanipulasi percakapan, dan menyusun strategi. Namun empatinya bukan empati yang tumbuh dari pengalaman, melainkan hasil simulasi yang dingin. Pintar, tapi tidak hangat.
Drama Korea pun sering mengambil pendekatan serupa. Dalam Are You Human Too?, robot Nam Shin III dibuat untuk menggantikan manusia. Ia sopan, stabil, dan nyaris sempurna. Ironisnya, justru ketidaksempurnaannya—ketika ia belajar merasakan dan ragu—yang membuatnya terasa lebih “manusiawi” dibanding manusia asli yang egois dan impulsif.
Cerita-cerita ini seolah mengingatkan: kepintaran saja tidak cukup. Ada sesuatu yang hanya tumbuh lewat proses yang lambat dan tidak efisien.
Budaya Hidup Cepat dan Tekanan untuk Selalu Pintar
Masalahnya, gaya hidup modern justru memuja kecepatan. Jawaban cepat dianggap cerdas. Keraguan dianggap kelemahan. Berpikir terlalu lama sering disalahartikan sebagai tidak kompeten.
AI hadir sebagai simbol puncak dari budaya ini. Ia tidak ragu. Tidak bimbang. Tidak overthinking. Selalu punya jawaban.
Tanpa sadar, standar itu ikut membebani manusia. Di dunia kerja, di media sosial, bahkan dalam obrolan santai, ada tekanan untuk selalu terdengar yakin. Tidak banyak ruang untuk berkata, “masih mikir,” atau “kayaknya ini belum tepat.”
Padahal, riset matematika yang dilakukan Hairer dan timnya justru menunjukkan kebalikannya. Dalam eksperimen soal-soal riset asli, AI sering memberikan jawaban panjang dan meyakinkan, tapi rapuh di bagian paling penting. Di tengah pembuktian, AI cenderung “mengarang” dan berharap pembaca tidak terlalu teliti.
Di titik ini, AI justru mirip manusia yang terlalu ingin terlihat pintar.
AI sebagai “Yes Man” dan Masalah dalam Hidup Sehari-hari
Salah satu kritik paling menarik dari riset tersebut datang dari Tamara Kolda, peneliti dari MathSci.ai. Ia menyebut AI sebagai yes man. AI tidak membantah. Tidak menantang sudut pandang pengguna. Selalu mengikuti arah yang diminta.
Dalam sains, ini masalah besar. Kemajuan lahir dari debat, dari ide yang saling bertabrakan. Tapi dalam kehidupan sehari-hari, kita juga sering terjebak dalam pola serupa.
Algoritma media sosial, misalnya, cenderung memperkuat apa yang sudah kita percaya. Jarang menantang, lebih sering mengiyakan. Lama-lama, hidup terasa rapi, tapi dangkal.
Film The Matrix sudah lama menyindir ini. Dunia yang terlihat nyaman dan tertata justru membatasi kebebasan berpikir. Kenyamanan tanpa konflik membuat manusia berhenti bertanya.
Terjebak Lingkaran dan Ketakutan Salah
Dalam eksperimen matematika, AI sering terjebak dalam infinite loop: menjawab, mengoreksi diri, menjawab lagi, lalu mengoreksi lagi tanpa pernah sampai ke solusi akhir.
Aneh tapi akrab.
Bukankah manusia modern juga sering mengalami hal serupa? Terlalu banyak informasi, terlalu banyak “jawaban pintar”, hingga akhirnya terjebak ragu dan tidak bergerak ke mana-mana.
Drama seperti Black Mirror berulang kali menyoroti ini. Teknologi yang seharusnya membantu justru memperbesar kecemasan, karena manusia kehilangan kepercayaan pada prosesnya sendiri.
Berani Lambat di Dunia yang Terlalu Cepat
Mungkin inilah titik penting yang sering terlupakan. Manusia tidak dirancang untuk selalu cepat. Berpikir, memahami, dan mencipta memang proses yang berantakan.
AI unggul dalam kecepatan. Tapi manusia unggul dalam perjalanan.
Matematika tingkat tinggi, seni, film, bahkan hubungan antarmanusia tumbuh dari kegagalan, kebuntuan, dan percakapan yang tidak selalu produktif. Dari debat yang melelahkan. Dari ragu yang panjang.
Di JUNG_E, film Korea tentang AI dan perang, pertanyaan terbesarnya bukan tentang seberapa canggih teknologi, tapi tentang apa yang hilang ketika keputusan hidup dan mati diserahkan pada mesin.
Pertanyaan yang sama relevan dalam hidup sehari-hari: sejauh mana kita ingin menyerahkan proses berpikir kepada sesuatu yang selalu tampak lebih pintar?
Hidup Bersama AI, Bukan Dikalahkan Olehnya
Artikel ini bukan ajakan untuk menolak AI. Justru sebaliknya. AI adalah alat yang luar biasa. Membantu belajar, merangkum, dan membuka akses informasi.
Tapi ada batas yang perlu disadari.
AI bisa mempercepat jawaban. Manusia memberi makna pada pertanyaan.
AI bisa terlihat yakin. Manusia berani ragu, lalu menemukan jalan baru.
Mungkin, di tengah dunia yang makin cepat dan efisien, keberanian terbesar manusia justru adalah berani berjalan pelan. Berani tidak langsung tahu. Berani salah.
Dan selama manusia masih mau berpikir dengan cara itu, cerita—baik di matematika, film, maupun hidup sehari-hari—akan selalu punya ruang yang tidak bisa digantikan mesin.